OPINI
OPINI: Paradoks BUMN: Aset Strategis yang Terkikis Politisasi
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan pilar strategis ekonomi Indonesia yang berperan sebagai instrumen pembangunan
Oleh: Umar, S.E., M.M.
Dosen dan Peneliti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palu
TRIBUNPALU.COM - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan pilar strategis ekonomi Indonesia yang berperan sebagai instrumen pembangunan, penyedia layanan publik, dan stabilisator ekonomi.
Namun, di balik potensi besarnya, BUMN menghadapi paradoks fundamental yang menggerogoti kinerjanya dari dalam.
Tesis utama dari analisis ini adalah BUMN, yang seharusnya dikelola untuk kemakmuran rakyat, kini telah dikooptasi oleh kepentingan politik partisan.
Fenomena ini terwujud melalui praktik sistematis penunjukan individu dengan afiliasi politik yang kuat, seperti politisi dan tim sukses pemilu, ke dalam jajaran dewan komisaris.
Praktik ini telah mengubah fungsi pengawasan menjadi ajang transaksi kekuasaan, di mana loyalitas politik menggantikan meritokrasi dan profesionalisme.
Baca juga: Siswi SMAN Model Madani dan SMA Kristen Gamaliel Palu Raih Duta Muda BPJS Kesehatan Palu 2025
Bukti empiris menunjukkan bahwa politisasi di dewan komisaris BUMN bukanlah anomali, melainkan sebuah pola yang meluas.
Analisis kuantitatif dari Transparency International Indonesia (TII) mengungkap gambaran yang mengkhawatirkan: dari total posisi komisaris yang diteliti, hanya 23.7 persen yang berlatar belakang profesional murni.
Sebaliknya, dewan komisaris justru didominasi oleh politisi (29.4 % ) dan birokrat (31 % ), yang pengangkatannya sering kali juga bersifat politis.
Kondisi ini membuktikan bahwa BUMN telah menjadi arena pembagian kekuasaan atau spoils system pasca-pemilu, di mana jabatan strategis digunakan sebagai "balas jasa" politik, bukan berdasarkan kompetensi manajerial.
Masalah ini diperparah oleh masifnya praktik rangkap jabatan yang secara efektif melembagakan konflik kepentingan.
Riset Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan bahwa lebih dari separuh (53.9 % ) komisaris BUMN terindikasi merangkap jabatan.
Praktik ini paling banyak dilakukan oleh pejabat aktif dari kementerian yang seharusnya berfungsi sebagai regulator, seperti Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan.
Situasi ini menciptakan anomali tata kelola yang fatal, di mana regulator sekaligus menjadi pihak yang diawasi.
Hal ini memastikan pengawasan menjadi lemah dan kebijakan rentan menjadi bias untuk melayani kepentingan pihak tertentu, bukan kepentingan perusahaan.
Kegagalan Tata Kelola dalam Tinjauan Manajemen Keuangan
Kegagalan tata kelola ini bermanifestasi langsung pada kinerja keuangan yang terukur.
Data menunjukkan tren penurunan efisiensi BUMN, terlihat dari merosotnya rasio Return on Equity (ROE) dari 10.8 % menjadi 9.3?n Return on Assets (ROA) dari 3.2 % menjadi 2.8?lam satu tahun. Ironisnya, penurunan efisiensi ini terjadi di tengah lonjakan utang yang masif.
Kombinasi peningkatan utang yang drastis dengan penurunan profitabilitas merupakan gejala klasik misalokasi modal, yang mengindikasikan bahwa keputusan investasi lebih didorong oleh agenda politik non-komersial daripada kelayakan bisnis yang sehat.
Teori Agensi (Jensen & Meckling, 1976), menjelaskan hubungan antara pemegang saham (prinsipal) dan manajemen (agen) diwarnai oleh potensi konflik kepentingan.
Dewan komisaris dibentuk sebagai mekanisme pengawasan untuk memastikan agen (manajemen) bertindak demi kepentingan terbaik prinsipal (negara/publik) dan untuk memitigasi biaya agensi (agency costs).
Namun, ketika dewan komisaris diisi oleh individu dengan afiliasi politik, struktur ini menjadi rusak. Muncul "prinsipal kedua" yang tidak terlihat, yaitu partai politik atau patron politik.
Akibatnya, komisaris yang seharusnya menjadi pengawas bagi negara, kini memiliki insentif ganda: mengawasi manajemen sambil memastikan tindakan manajemen juga sejalan dengan kepentingan prinsipal kedua.
Konflik kepentingan ini menjadi tak terhindarkan. Keputusan investasi mungkin tidak lagi didasarkan pada analisis Net Present Value (NPV) yang positif, melainkan pada proyek-proyek yang memiliki visibilitas politik tinggi. Kebijakan rekrutmen mungkin lebih mengutamakan afiliasi daripada kompetensi.
Fungsi pengawasan yang seharusnya tajam menjadi tumpul karena loyalitas telah terbagi.
Baca juga: DPRD Minta Pemda Parigi Moutong Realisasikan Hasil Reses dan Laporkan Secara Tertulis
Runtuhnya mekanisme kontrol ditinjau dari analisis teori pengendalian. Teori Pengendalian (Control Theory) dalam manajemen berfokus pada sistem dan mekanisme yang dirancang untuk menjaga organisasi tetap pada jalurnya dalam mencapai tujuan strategisnya.
Mekanisme ini mencakup pengendalian internal, audit independen, dan yang terpenting, pengawasan oleh dewan yang objektif. Dewan komisaris yang didominasi oleh unsur politik secara sistematis melemahkan mekanisme kontrol ini.
Alih-alih berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan eksekutif (checks and balances), dewan tersebut justru dapat menjadi fasilitator bagi keputusan-keputusan yang didorong oleh motif politik, yang sering kali mengabaikan prosedur standar keuangan dan operasional.
Risiko penipuan (fraud), alokasi sumber daya yang tidak efisien, dan penyimpangan strategis dari tujuan komersial yang sehat meningkat secara eksponensial. Ketika kontrol internal dilemahkan dari atas, budaya kepatuhan di seluruh organisasi terkikis.
Pergeseran fungsi dari pelayan menjadi partisan merupakan sebuah distorsi dalam pandangan teori stewardship.
Berbeda dengan Teori Agensi yang berasumsi adanya konflik kepentingan, Teori Stewardship (Davis, Schoorman & Donaldson, 1997) mengasumsikan bahwa para direktur dan komisaris adalah "pelayan" (stewards) yang secara intrinsik termotivasi untuk bertindak demi kepentingan jangka panjang perusahaan. Kepentingan mereka dianggap selaras dengan kepentingan organisasi.
Namun, asumsi fundamental ini runtuh ketika proses seleksi komisaris tidak didasarkan pada rekam jejak profesional dan integritas, melainkan pada loyalitas politik.
Motivasi utama mereka mungkin bukan lagi menjadi pelayan aset negara, melainkan memenuhi kewajiban politik atau "balas jasa". Peran mereka bergeser dari mitra strategis manajemen menjadi pengawas politik.
Hal ini mendistorsi budaya perusahaan secara keseluruhan, dari budaya yang berorientasi pada kinerja (performance-driven) menjadi budaya yang berorientasi pada kepatuhan terhadap tuntutan politik eksternal.
Kegagalan yang dijelaskan oleh ketiga teori ini tidak terjadi secara terpisah.
Sebaliknya, mereka saling terkait dan saling memperkuat, menciptakan sebuah siklus setan kerusakan tata kelola (vicious cycle of governance decay).
Proses ini dimulai ketika penunjukan politik merusak fungsi pengawasan dalam Teori Agensi. Dengan pengawasan yang lemah, mekanisme kontrol internal yang dijelaskan dalam Teori Pengendalian menjadi mudah untuk dilewati demi keputusan yang menguntungkan secara politik tetapi merugikan secara komersial.
Lingkungan kerja yang tidak profesional ini secara aktif menolak atau mengeluarkan para "pelayan" sejati yang diidealkan dalam Teori Stewardship.
Manajer profesional yang tersisa terpaksa harus "bermain politik" untuk bertahan, yang semakin mengikis budaya profesional perusahaan.
Ironisnya, kinerja buruk yang dihasilkan dari siklus ini sering kali digunakan oleh aktor politik sebagai pembenaran untuk melakukan intervensi yang lebih besar lagi dengan dalih "memperbaiki masalah", yang pada kenyataannya hanya memperdalam politisasi dan memulai kembali siklus tersebut dengan intensitas yang lebih tinggi.
Kontras Internasional dan Urgensi Depolitisasi Struktural
Kontras dengan situasi di Indonesia, banyak negara telah berhasil membangun sektor BUMN yang profesional, kompetitif, dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian tanpa terjerat oleh intervensi politik yang berlebihan.
Laporan dari OECD (2024) menyoroti keberhasilan Korea Selatan dan Singapura sebagai contoh utama.
Di kedua negara tersebut, penerapan mekanisme seleksi dewan komisaris yang ketat berbasis kompetensi telah terbukti menghasilkan peningkatan Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE) hingga mencapai dua digit dalam lima tahun terakhir.
Keberhasilan ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari desain institusional yang cermat untuk mengisolasi BUMN dari campur tangan politik.
Model Singapura (Temasek): Singapura menggunakan struktur perusahaan induk (holding company) independen seperti Temasek Holdings.
Temasek bertindak sebagai pemegang saham aktif yang berorientasi komersial dan menjadi penyangga (buffer) yang efektif antara pemerintah (sebagai pemilik utama) dan manajemen operasional BUMN.
Dewan direksi dan komisaris di perusahaan-perusahaan portofolio Temasek diisi oleh para pemimpin bisnis internasional yang terbukti, dengan mandat yang jelas untuk memaksimalkan nilai pemegang saham jangka panjang.
Model Korea Selatan: Korea Selatan memperkuat independensi BUMN melalui pembentukan komite nominasi yang kuat dan independen.
Komite ini menggunakan kriteria berbasis kompetensi yang jelas dan transparan untuk menyeleksi calon anggota dewan.
Terdapat pemisahan yang tegas antara peran negara sebagai pemegang saham dan peran negara sebagai regulator, untuk mencegah konflik kepentingan.
Masalah tata kelola BUMN di Indonesia bukanlah karena ketiadaan regulasi.
UU BUMN No. 19 Tahun 2023, misalnya, telah menyediakan kerangka hukum yang membatasi penunjukan pejabat politik. Namun, tantangan terbesarnya terletak pada kesenjangan implementasi (implementation gap) yang parah.
Aturan yang ada sering kali dilemahkan oleh kurangnya kemauan politik (political will) untuk menegakkannya secara konsisten.
Oleh karena itu, inti dari reformasi bukanlah sekadar menciptakan undang-undang baru, melainkan membangun mekanisme penegakan yang kuat, independen, dan kebal dari tekanan politik.
Untuk membalikkan tren yang merusak ini, diperlukan reformasi struktural yang berfokus pada akar masalah. Rekomendasi utamanya meliputi tiga pilar.
Pertama, reformasi institusional dengan membentuk perusahaan induk BUMN yang independen dan profesional seperti model Temasek untuk menjadi penyekat dari intervensi politik.
Kedua, reformasi hukum dengan mengamandemen UU BUMN untuk memperluas definisi konflik kepentingan secara substantif.
Ketiga, reformasi transparansi dengan membentuk komite nominasi independen dan portal data publik yang komprehensif.
Namun, keberhasilan seluruh reformasi teknis ini pada akhirnya bergantung pada satu faktor krusial: kemauan politik dari pimpinan negara untuk melepaskan kendali atas BUMN sebagai alat patronase.(*)
| Validasi Data, Garis Kemiskinan dan Integrasi Program Jadi Kunci Utama Strategi Penangan Kemiskinan |

|
|---|
| Pertanian di Tanah Kaili, Daya Saing atau Sekadar Slogan? |

|
|---|
| Regenerasi Pertanian Nasional dari Timur Indonesia |

|
|---|
| OPINI : Dokter Jantung Anak Hanya untuk yang Mampu? Potret Buram Akses Kesehatan Publik |

|
|---|
| OPINI: Korupsi Pendidikan Menggerus Kesehatan Mental Generasi Emas |

|
|---|










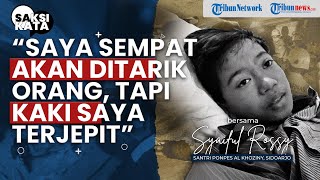





Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.